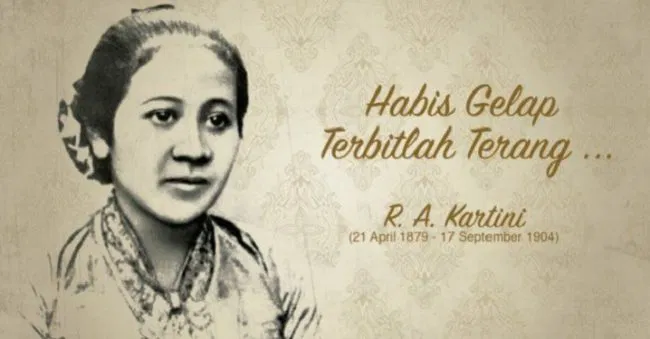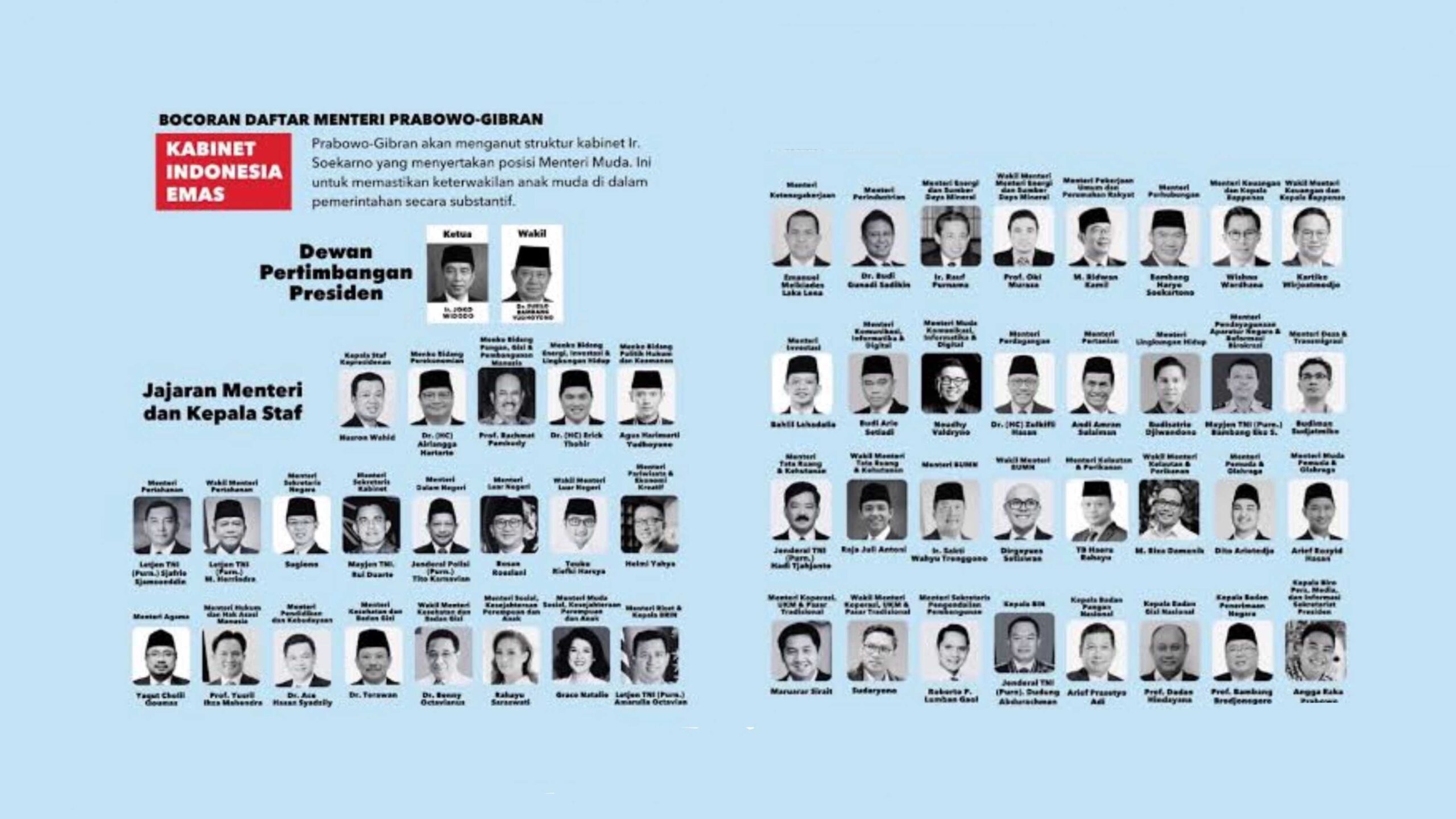Selasa, 23 Syawal 1446 H/ 22 April 2025
Oleh: DR. Payamta, dosen FEB UNS dan pemerhati masalah Pendidikan
Raden Ajeng Kartini, melalui kumpulan suratnya yang dihimpun dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang, telah menyalakan obor pencerahan di tengah kegelapan penindasan kolonial dan belenggu adat yang mengekang perempuan pribumi. Ia lahir pada 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah, pada masa ketika Hindia Belanda masih dikuasai oleh pemerintahan kolonial Belanda di bawah kebijakan tanam paksa yang masih menyisakan dampak panjang terhadap kehidupan rakyat Indonesia. Kartini adalah suara hati nurani yang menggema dari masa penjajahan, menembus waktu,
Surat-surat yang ia tulis antara tahun 1899 hingga 1904 mengandung refleksi mendalam mengenai penderitaan rakyat, keterbelakangan pendidikan, dan keterkungkungan perempuan pribumi. Ia menggugat ketidakadilan budaya dan agama yang dibajak oleh tafsir patriarkal, serta mengungkapkan kerinduannya akan peradaban yang tercerahkan. Tulisan-tulisan ini kemudian dihimpun oleh J.H. Abendanon, Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Koloni Belanda, dan diterbitkan pada tahun 1911 dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang.
Konsep “dari gelap menuju terang” bukan sekadar metafora puitis. Dalam Al-Qur’an, Allah berfirman: “Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya” (QS. Al-Baqarah: 257). Ayat ini memuat makna transformatif: bahwa keimanan yang sejati mendorong manusia untuk keluar dari zhulumat (beragam bentuk kegelapan)—baik kebodohan, kezaliman, ketertindasan, maupun keputusasaan—menuju nur, yakni pencerahan, keadilan, dan kemerdekaan jiwa.
Makna tersebut sangat kontekstual dengan kehidupan R.A. Kartini. Sebagai perempuan Jawa bangsawan di masa penjajahan Belanda pada akhir abad ke-19, Kartini tumbuh dalam dunia yang gelap—bukan hanya secara politis di bawah kolonialisme, tetapi juga secara sosial dan budaya yang menindas perempuan. Dalam dunia seperti itu, agama pun sering kali dipraktikkan secara simbolik dan tekstual, tanpa menyentuh makna pembebasan yang sejatinya melekat dalam ajaran Islam. Meski lahir dari keluarga Islam dan dibesarkan dalam lingkungan priyayi Jawa, Kartini mengaku dalam surat-suratnya bahwa ia sempat merasa kecewa terhadap agama. Dalam suratnya kepada Stella (Stella Zeehandelaar), Kartini menulis: “Agama sering dipakai untuk membelenggu perempuan. Kami menginginkan pendidikan, tetapi mereka berkata: agama melarangnya.” Ini menunjukkan kegelisahan spiritual Kartini terhadap institusi agama yang menurutnya saat itu, lebih banyak digunakan untuk mempertahankan tatanan sosial patriarkal.
Namun titik balik penting dalam spiritualitas Kartini terjadi ketika ia mulai belajar tafsir Al-Qur’an dalam bahasa Jawa dari seorang ulama besar, K.H. Soleh Darat. Dalam banyak catatan sejarah, disebutkan bahwa Kartini sangat terkesan ketika membaca terjemahan dan tafsir Surah Al-Fatihah dan Surah Al-Baqarah karya Kyai Soleh Darat yang ditulis dalam aksara pegon. Saat itu, Al-Qur’an belum diterjemahkan secara luas ke dalam bahasa lokal karena dianggap tabu. Kyai Soleh Darat mematahkan tabu itu, dan menjadikan Kartini sebagai saksi penting kebangkitan Islam yang lebih transformatif.
Dalam pengantar salah satu kitab tafsirnya, Kyai Soleh Darat menulis:
“Ilmu tanpa amal adalah sia-sia, amal tanpa ilmu adalah kesesatan.” Kalimat ini sangat sesuai dengan semangat “Habis Gelap Terbitlah Terang”—sebuah jalan menuju pencerahan yang dimulai dari pembelajaran, pemahaman, dan penerjemahan nilai-nilai Ilahi ke dalam tindakan sosial. Kartini pun mulai menyadari bahwa ajaran Islam sejatinya membebaskan manusia dari belenggu ketertindasan dan kebodohan. Ia kemudian menggunakan pemahamannya ini sebagai landasan moral dan spiritual dalam memperjuangkan cita-cita: pendidikan bagi kaum perempuan, kesetaraan martabat manusia, dan kemerdekaan berpikir.
Namun dalam sistem yang serba membatasi perempuan seperti saat itu, Kartini tidak bisa turun langsung ke lapangan atau terlibat dalam aktivitas politik secara formal. Ia memilih strategi yang halus, tapi berdampak besar: menulis surat, membangun wacana, dan mendirikan sekolah. Pada tahun 1903, Kartini berhasil mendirikan Sekolah Kartini di Jepara, bekerja sama dengan pemerintah kolonial yang mulai menerapkan Politik Etis. Meski dengan banyak keterbatasan, sekolah Ini adalah langkah konkret menuju “terang” yang ia cita-citakan. Strategi penanya yang tajam dan argumentatif juga menjadi kekuatan utama. Melalui surat-surat yang ia kirim kepada para sahabatnya di Belanda, Kartini membongkar hipokrisi sistem kolonial dan adat feodal. Surat-surat Kartini adalah “renungan-renungan yang melampaui zamannya”, yang tak hanya berbicara soal perempuan, tetapi juga tentang hakikat manusia dan masa depan bangsa.
Dengan demikian, perjuangan Kartini sejatinya adalah penerapan nyata dari ajaran transformatif Al-Qur’an. Ia berjalan dari zhulumat—pengasingan, ketertindasan budaya, kebodohan sistematis—menuju nur: pembebasan, pendidikan, dan kesadaran nilai-nilai kemanusiaan universal. Kartini bukan hanya sosok lokal, tapi bagian dari gerakan pencerahan dunia yang digerakkan oleh iman, ilmu, dan cinta kepada sesama.
Wallahu a’lam bishshawab